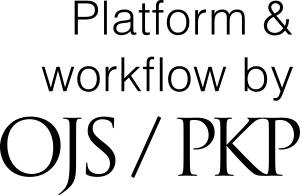TINJAUAN BUKU POLITIK WACANA BUDAYA KEBERSIHAN DALAM PASCAKOLONIAL INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.660Abstract
Kebersihan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan sering kali menjadi prasyarat dalam pergaulan dan interaksi sosial. Seseorang dikatakan bersih bisa dilihat dari penampilan, baik itu cara berpakaian, tata krama yang dipraktikkan, maupun cara menggunakan perangkat makan, seperti sendok dan garpu, serta cara menyikapi kondisi tubuh dalam mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh (misalnya, ketika batuk, mengeluarkan dahak, ataupun bersin). Di sisi lain, kebersihan bisa menjadi penanda tingkat pendidikan seseorang, apakah ia bisa dikategorikan sebagai “modern” atau “tradisional”, berpendidikan atau kurang berpendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 180-181), kata bersih, secara harfiah, diartikan ‘bebas dan tidak tercemar dari kotoran, serta tidak tercampur unsur zat lain’. Sementara itu, kata kebersihan lebih merujuk pada ‘perihal keadaan bersih, suci, murni, dan kepercayaan manusia yang tidak mengandung noda, kotoran, ataupun dosa’. Di sini, kebersihan tidak hanya menyangkut lingkungan, tapi juga pengelolaan tubuh terkait sesuatu yang berada ataupun di dalam yang mesti dihilangkan. Tidak ada definisi yang ketat mengenai kebersihan dan maknanya, dalam hal dan konteks apa sesuatu ataupun seseorang dianggap bersih. Alasannya, wacana kebersihan lebih menyangkut dengan cara pandang, dan bagaimana cara pandang itu dikonstruksi dan direproduksi, yang dapat membentuk pemahaman seseorang atas apa yang dianggap bersih dan kotor. Melalui mekanisme ini makna kebersihan diartikulasikan. Bagi orang yang bergayahidup di perkotaan, misalnya, membuang ludah di sembarang tempat tidak hanya dianggap jorok, tetapi tidak berbudaya dan dianggap kampungan. Agar terlihat santun dan beradab, seseorang yang membuang ludah menggunakan sapu tangan ataupun tisu, lalu disimpan di saku baju bila tidak menemukan tempat sampah. Sebaliknya, bagi orang yang hidup di pinggiran kota besar dan perdesaan, membuang ludah bisa di mana saja, asalkan tidak di dalam rumah. Alasannya, ludah adalah kotoran yang harus dibuang segera. Ia tidak terlalu memikirkan apakah tindakan itu berbudaya atau tidak. Justru, baginya, orang tidak dianggap berbudaya ketika menyimpan ludah di sapu tangan ataupun tisu lalu menyimpannya ke dalam saku. Definisi kebersihan dan posisi orang yang lebih berbudaya menjadi relatif terkait dengan cara pandang dan relasi sosial yang bersinggungan dalam memaknai kebersihan. Untuk lebih jelas mengetahui bagaimana kebersihan dikonstruksi dan direpro duksi massal, kita bisa melihat iklan produk pembersih. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, saat televisi hanya memiliki satu jaringan, TVRI, kita hanya mengenal dua produk pembersih. Sabun mandi yang digunakan untuk membasuh seluruh permukaan badan, termasuk wajah. Sabun batangan yang digunakan untuk keperluan mencuci pakaian, peralatan memasak, dan perkakas dapur. Melalui iklan televisi, kita dihadapkan pada pelbagai macam produk pembersih yang sudah terspesialisasikan. Tiap-tiap produk tersebut dianggap memiliki kegunaan untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran dan noda dari setiap anggota tubuh dan barang yang kita gunakan. Melalui dramatisasi dalam mengonstruksi kuman dan bakteri yang terdapat dalam kotoran, iklan-iklan tersebut berusaha menciptakan efek filmis untuk memengaruhi kita agar berhati-hati dan tetap menjaga kebersihan dalam situasi apa pun. Dengan visualisasi yang kuat, iklan tersebut seakan meneguhkan bahwa “juru selamat” penghindar dari kotoran yang mengandung bakteri dan kuman adalah produk-produk pembersih mereka (Dovita 2011). Penjelasan di atas adalah wacana kebersihan melalui praktik-praktik budaya populer dalam konteks kekinian, khususnya pascarezim Orde Baru. Bagaimana dengan wacana kebersihan dalam sejarah Indonesia, khususnya fase kolonial Belanda yang sangat memengaruhi watak dan budaya masyarakat Indonesia kebanyakan hingga saat ini? Buku hasil dari konferensi, dipimpin oleh Kees van Dijk dan disponsori oleh KTILV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Carribbean, Leiden, Belanda, setidaknya bisa menjawab pertanyaan itu. Buku yang terdiri dari tujuh bab, ditulis oleh akademisi Belanda dan Australia, dapat membantu pembaca memahami wacana kebersihan masa Hindia Belanda dipraktikkan dan digunakan untuk mengonstruksi atas apa yang dianggap bersih dan kotor. Selain itu, melalui buku ini, pembaca akan ditunjukkan makna kebersihan bagi orang Indonesia kebanyakan, khususnya di daerah Jawa dan perubahan makna kebersihan dengan berkiblatnya orang-orang Barat ke dunia Timur, melalui spa (lulur, mandi air hangat, dan pijat refleksi). Untuk mempermudah pembahasan tinjauan buku tersebut, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu studi poskolonial sebagai pijakan yang digunakan dalam mendiskusikan buku ini. Kedua, dinamika wacana kebersihan sebagai pembahasan utama yang membentuk identitas kelas dan ideologi. Ketiga, penutup, yang berisi catatan konstruktif terhadap isi buku ini dengan memberikan sejumlah masukan.
References
Abdul Kadir, Hatib. 2012. “Budaya Kebersihan dalam Sejarah Indonesia”, dalam Review Buku Cleanliness and Culture Indonesian Histories (ed. Kees van Dijk dan Jean Gelman Taylor, 28 Februari 2012, http://etnohistori.org/budayakebersihan-dalam-sejarah-indonesia-review-hatib-abdul-kadir.html, diakses 9 November 2012.
Budianta, Melani. 2002. “Teori Sastra Sesudah Strukturalisme: Dari Studi Teks ke Studi Wacana Budaya”. PPKB LPUI dalam Pelatihan Teori dan Kritik Sastra, PPPG Bahasa 27-30 Mei 2002.
Dovita, Maria. 2011. “Kotor itu Duit: Cerita Soal Produk Pembersih di Televisi”, http:// remotivi.or.id/pendapat/kotor-itu-duit, dikutip 1 November 2012
Leela, Gandhi.1998 . Postcolonial Theory: A Critical Introduction. St. Leonadrds: Allen & Unwin.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2012 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.